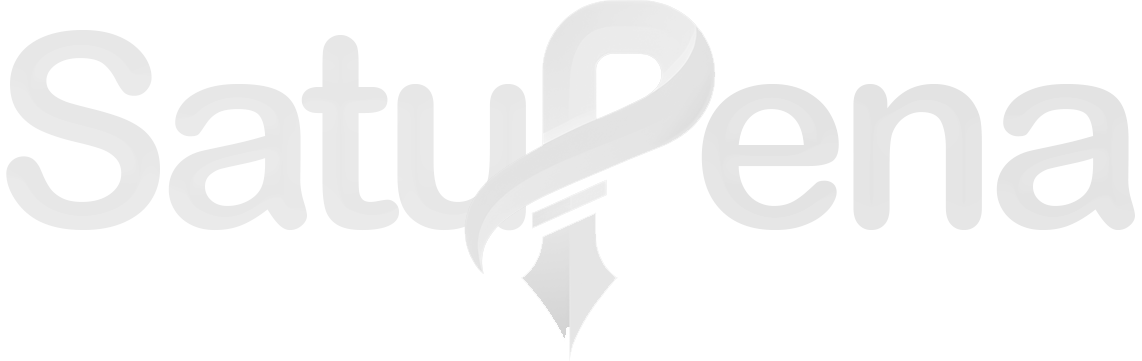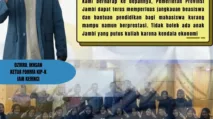Oleh: Dr. Noviardi Ferzi
Rencana pembangunan terminal batubara PT. SAS di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi, menyingkap kelemahan serius dalam sistem perizinan dan tata kelola ruang di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek legalitas izin, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Berdasarkan data yang beredar, lahan ±47,6 hektare yang diajukan PT. SAS justru masuk ke dalam peruntukan ruang yang jelas tidak sejalan dengan fungsi terminal batubara: kawasan lindung 30 persen, perumahan 56 persen, ketahanan pangan 9 persen, dan perdagangan-jasa 5 persen. Fakta ini bertentangan dengan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dengan RTRW. Jika izin tetap dibiarkan, maka secara hukum izin tersebut berpotensi cacat. Lebih jauh, hal ini juga mengingkari semangat Undang-Undang Cipta Kerja yang meskipun memberikan kemudahan investasi, tetap menggariskan prinsip kepatuhan terhadap tata ruang dan kelestarian lingkungan.
Sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) memang dirancang untuk memangkas birokrasi. Namun Pasal 17 PP Nomor 21 Tahun 2021 memberi ruang bagi daerah yang belum memiliki RDTR untuk melakukan persetujuan KKPR melalui kajian teknis manual. Celah inilah yang rawan disalahgunakan. Pertanyaan publik sangat relevan: apakah dokumen PT. SAS benar diverifikasi secara substansial, ataukah hanya sebatas formalitas administratif? Di sinilah potensi maladministrasi mencuat. Bila terbukti ada manipulasi atau kelalaian, maka kasus ini dapat dikategorikan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana yang merugikan kepentingan publik.
Penolakan warga sekitar yang disertai surat resmi Pemko Jambi kepada Gubernur menjadi bukti nyata resistensi lokal. Aktivitas land clearing dan penimbunan material yang sudah berlangsung memperkuat dugaan pelanggaran tata ruang dan aturan lingkungan. Terminal batubara, selain berpotensi menimbulkan polusi udara dan kebisingan, juga akan menekan kualitas lingkungan hidup kawasan pemukiman yang semestinya dilindungi. Apabila proses pembangunan tetap dilanjutkan, konflik sosial sulit dihindari. Masyarakat yang merasa ruang hidupnya terancam bisa mengambil langkah hukum, bahkan melakukan perlawanan sosial yang dapat merugikan iklim investasi secara keseluruhan.
Jika benar KKPR dikeluarkan tanpa dasar tata ruang yang sah, maka unsur maladministrasi jelas ada. Hal ini sesuai dengan definisi maladministrasi dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Lebih jauh, jika terbukti ada rekayasa dokumen, kasus ini bisa mengarah pada dugaan korupsi perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pertama, tanggung jawab utama berada di pemerintah pusat. Kementerian Investasi/BKPM sebagai penerbit KKPR melalui OSS, dan Kementerian ATR/BPN sebagai otoritas tata ruang, wajib melakukan audit izin. Berdasarkan Pasal 22 PP 21/2021, ATR/BPN berwenang membatalkan KKPR yang menyimpang. Kedua, pemerintah provinsi memiliki peran krusial. Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) UU Penataan Ruang menyebut gubernur memiliki kewenangan koordinasi lintas wilayah dan bahkan kewenangan membatalkan izin yang bertentangan dengan RTRW provinsi maupun RTRW kabupaten/kota. Gubernur Jambi tidak bisa hanya menjadi penonton. Ketiga, pemerintah kota juga tidak boleh lepas tangan. Walikota sebagai pemegang otoritas tata ruang kota wajib mengawasi, menertibkan, dan melaporkan pelanggaran kepada kementerian terkait. Diamnya Pemkot bisa dianggap kelalaian serius dan berpotensi menyeret mereka ke dalam persoalan hukum tata ruang.