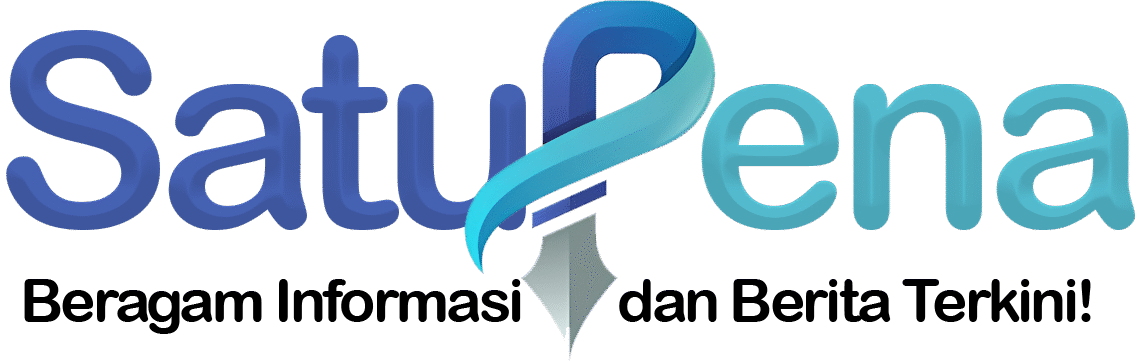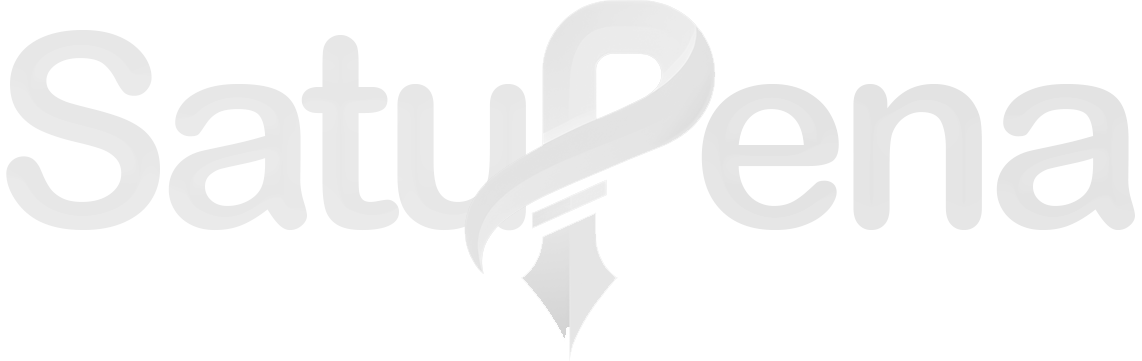Opini: Randi Vitora
Jika kita berdiri di pinggir jalan raya Kerinci atau di sudut Kota Sungai Penuh hari ini, kita akan melihat pemandangan yang sama: truk sampah yang lewat dengan muatan penuh. Bagi sebagian besar dari kita, pemandangan itu memberikan rasa lega palsu—seolah-olah dengan hilangnya kantong plastik dari depan rumah, masalahnya selesai. Namun, kenyataannya kita hanya sedang memindahkan bom waktu dari satu titik ke titik lain.
Sebagai aktivis lingkungan, saya menganalogikan secara sederhana. Pengelolaan sampah kita saat ini ibarat mencoba mengeringkan lantai yang banjir karena keran air yang terbuka lebar, tapi bukannya memutar keran untuk menutup aliran air, kita justru sibuk membeli ember yang lebih banyak dan pel yang lebih besar untuk memindahkan airnya ke ruangan sebelah. Ember dan pel itu adalah truk sampah dan tempat pembuangan akhir, sementara keran air yang terus mengucur deras adalah gaya hidup kita yang tak bisa lepas dari plastik sekali pakai. Sehebat apa pun kita mengepel, lantai tidak akan pernah kering selama kerannya tidak kita tutup.
Selama ini, kita terjebak dalam kekeliruan berpikir. Kita terlalu mengagungkan kata “daur ulang” seolah itu adalah jimat sakti. Padahal, daur ulang itu ibarat mengobati penyakit kronis yang sudah parah—biayanya mahal dan hasilnya tidak pernah sempurna. Mengapa kita tidak memilih untuk mencegahnya sejak awal?
Dan bahkan persoalan limbah rumah tangga saja sampai hari ini belum menemukan jalan keluar yang tuntas di Kerinci dan Sungai Penuh. Kini, kita dihadapkan pada tantangan baru yang melintas di depan mata: program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kita harus waspada, jangan sampai niat mulia memberi gizi bagi anak-anak kita justru meninggalkan warisan limbah yang merusak masa depan mereka. Tanpa konsep operasional yang ramah lingkungan, dapur-dapur MBG ini akan menjadi sumber masalah baru, sisa makanan akan menumpuk setiap harinya di sekolah-sekolah jika tidak dikelola dengan sistem yang benar atau bahkan melakukan pengomposan dari limbah tersebut.
Memasuki tahun 2026, saya harus jujur. Di sekepal tanah surga ini, kita seolah kehilangan kearifan lokal. Dulu, orang tua kita ke pasar membawa keranjang atau membungkus nasi dengan daun pisang. Kini, segalanya dibalut plastik yang hanya kita pegang 10 menit, namun merusak tanah hingga ratusan tahun. Kita terlalu fokus pada “bagaimana cara mengolahnya nanti” dan abai pada “kenapa kita harus memakainya sekarang”.
Para pemangku kebijakan perlu melihat ini dengan kacamata yang berbeda. Menambah armada truk bukanlah prestasi. Solusi konkret menuju 2026 haruslah berani: mulai dari larangan plastik sekali pakai di pasar, hingga mewajibkan dapur program MBG menggunakan sistem zero waste atau wadah yang bisa dicuci ulang.
Mari kita jadikan 2026 sebagai tahun di mana kita kembali ke dasar. Mengurangi (Reduce) dan memakai kembali (Reuse) harus menjadi gaya hidup. Jika kita terus memindahkan masalah tanpa menutup “kerannya”, maka kita tidak sedang mewariskan keindahan alam Kerinci untuk anak cucu, melainkan gunung sampah yang hanya tinggal menunggu waktu untuk longsor menimbun masa depan mereka.(*)