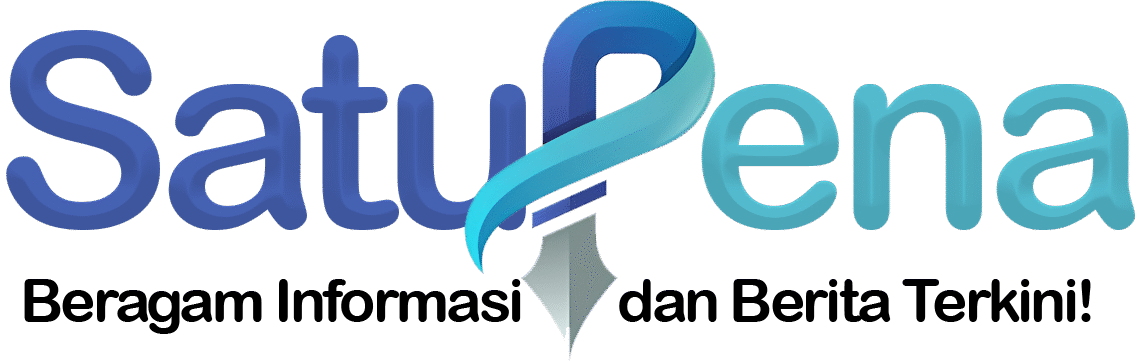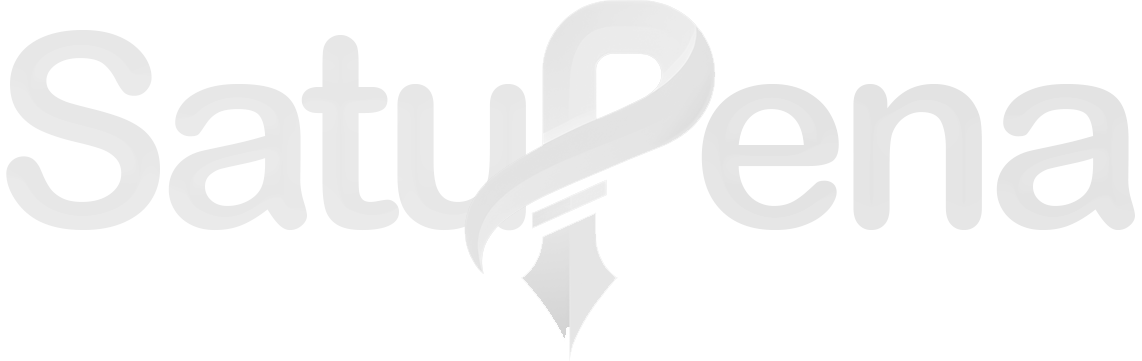Oleh :Ahmad Fadillah Zurdi mahasiswa Universitas Jambi
Dalam lanskap demokrasi Indonesia, politik sering didefinisikan sebagai arena pertarungan kepentingan. Namun pertanyaan mendasarnya adalah: kepentingan siapa yang sesungguhnya sedang diperjuangkan? Narasi-narasi politik hari ini lebih banyak digerakkan oleh elite yang memiliki kuasa atas modal, media, dan akses kebijakan. Ironisnya, yang paling lantang membela para elite itu justru rakyat miskin, yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat.
Kita menyaksikan realitas sosial yang absurd: rakyat yang terhimpit oleh mahalnya sembako, rendahnya upah, dan minimnya perlindungan sosial, justru menjadi garda terdepan dalam membela politisi yang duduk nyaman di kursi kekuasaan. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan rela berkonflik dengan tetangga, teman kerja, bahkan keluarganya sendiri hanya karena perbedaan pilihan politiks seolah-olah keberpihakan pada tokoh tertentu akan mengubah langsung nasib hidup mereka. Padahal yang berubah hanyalah siapa yang mencuri lebih lihai, bukan siapa yang benar-benar peduli.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari strategi penguasaan wacana oleh oligarki. Edward Said dalam Culture and Imperialism menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan, tetapi melalui produksi makna. Oligarki di Indonesia memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka menguasai media, membentuk opini, memproduksi rasa takut, dan menyuplai harapan palsu. Mereka membuat rakyat miskin percaya bahwa satu-satunya harapan mereka terletak pada figur-figur karismatik, bukan pada sistem yang adil. Dalam struktur semacam ini, rakyat bukan hanya dimiskinkan secara ekonomi, tapi juga secara nalar.
Yang lebih tragis adalah kecenderungan rakyat untuk saling menyalahkan satu sama lain. Ketika listrik mahal, bukan pemerintah yang disalahkan, tetapi tetangga yang dianggap tidak bersyukur. Saat BBM naik, bukan kebijakan yang dituntut, tetapi sesama warga yang disebut terlalu banyak mengeluh. Buruh memusuhi buruh, pedagang memaki demonstran, sopir ojek online mencaci mahasiswa. Solidaritas kelas yang seharusnya menjadi kekuatan rakyat, justru hancur oleh adu domba sistemik yang dilanggengkan oleh para elite.
Inilah keberhasilan besar oligarki: menjadikan rakyat miskin sebagai alat pembela kekuasaan yang menindas mereka, sekaligus membuat mereka menjadi algojo terhadap sesamanya. Politik kehilangan makna sebagai alat perubahan sosial, dan berubah menjadi arena sirkus tempat rakyat bersorak bukan atas keadilan, tetapi atas ilusi kemenangan palsu.
Maka satu-satunya harapan tersisa adalah: menumbuhkan kesadaran kritis. Bukan lewat slogan “cintai negeri ini” yang hampa makna, tetapi melalui pendidikan politik yang membumi, media alternatif yang progresif, dan gerakan akar rumput yang konsisten membongkar kepalsuan. Kita tidak bisa terus mengandalkan perubahan dari atas, jika yang di atas hanya sibuk membangun dinasti dan melanggengkan status quo.
Izinkan penulis mengutip nilai luhur dari ajaran agama: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya.” Kalimat ini memang sering keluar dari lisan para penceramah, namun sesungguhnya, yang paling berpeluang menjalankan ayat tersebut bukan hanya para ustaz, melainkan para pemimpin. Karena kekuasaanlah yang memiliki kapasitas terbesar untuk membuat kebijakan yang menyentuh kehidupan orang banyak. Maka celakalah seorang pemimpin yang pandai mengutip ayat, tapi membiarkan rakyatnya kelaparan, dan mengutuk rakyatnya sendiri karena dianggap “malas bersyukur.” Sebab kepemimpinan bukanlah tempat menumpuk citra, tetapi medan pembuktian nilai. Tutupnya (Guh)