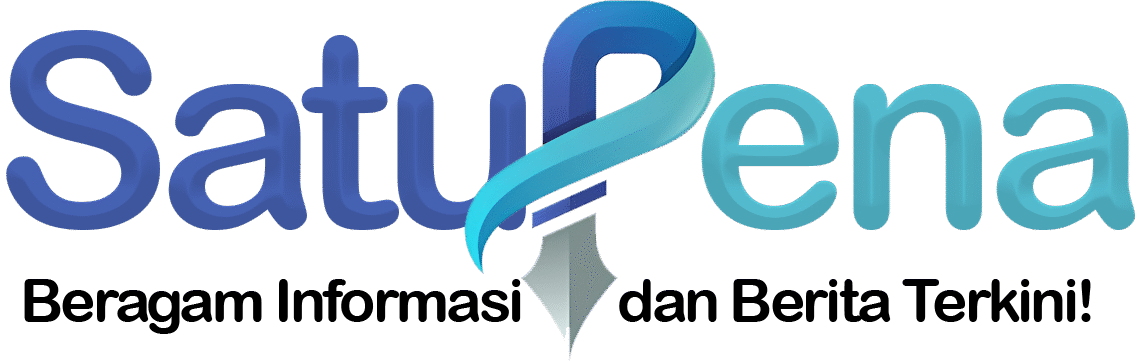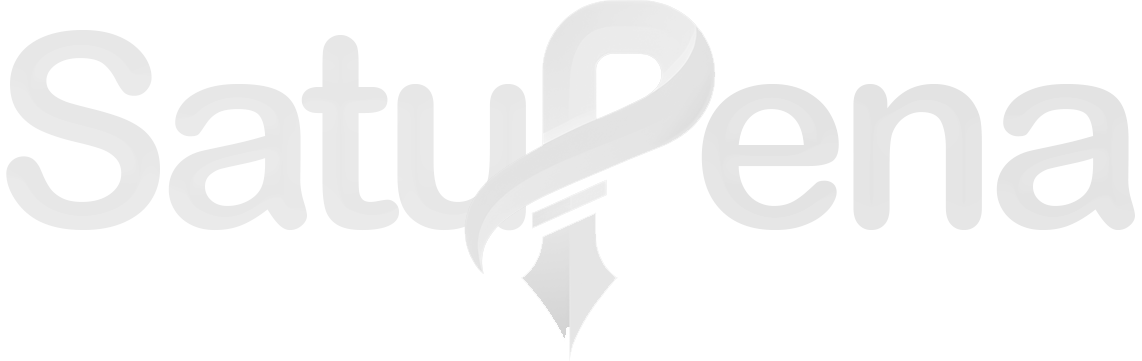Dengan bermodalkan kuota internet, kreativitas dalam desain visual maupun editing video, pada akhirnya mereka dapat menjangkau ribuan audiens. Hal itu pastinya lebih efektif, lebih cepat, dan lebih partisipatif ketimbang aksi yang dilakukan dalam ruang di lapangan terbuka ataupun melalui leaflet/selebaran.
Media sosial kini menjadi ruang tanpa sekat, lebih bebas, dan menjadi tempat yang dapat langsung menyuarakan aspirasi langsung ke pihak yang bersangkutan melalui akun-akun official mereka dan disaksikan oleh banyak orang dalam rupa sebagai netizen.
Mereka tak perlu mengajukan izin ataupun mengirimkan surat pemberitahuan untuk mengadakan aksi di lapangan. Gerakan aktivisme digital bisa langsung dilakukan secara instan dan mampu menarik atensi banyak orang. Bahkan, bagi pihak-pihak yang sebelumnya tidak berani menyampaikan aspirasi secara langsung, lewat media sosial bisa mereka lakukan. Baik secara terang-terangan ataupun melalui praktik anonimitas.
Waspada Penumpang Gelap dan Trial By Social Media
Namun, perlu diingat bahwa aktivisme digital tetap membutuhkan literasi digital yang kuat. Publik harus tetap aware, lebih bijak, tahu beda hoaks dan mana yang fakta. Publik juga harus cermat dan penting untuk tahu apakah suatu isu yang muncul karena viral benar adanya karena fakta dan demi kepentingan publik. Bukan justru viral karena adanya settingan tertentu ataupun ada praktik desain propaganda demi kepentingan segelintir orang.
Sesungguhnya aktivisme digital mengandung paradoks: ketika semangat menyuarakan kebenaran justru berpotensi melahirkan kebisingan tanpa arah, bahkan persekusi sosial yang menyalahi prinsip-prinsip keadilan. Hal itulah mestilah jadi perhatian kita bersama.
Di titik inilah edukasi kepada masyarakat dan peran jurnalisme menjadi krusial agar informasi yang diterima oleh masyarakat memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Di era ini, peran tersebut sangat krusial demi membangun ekosistem ruang publik digital yang sehat.
Kita harus tahu bahwa kampanye yang dilakukan secara digital tak bisa langsung dibaca secara simplisitis. Ada konsekuensi bentuk aktivisme tersebut cenderung mengalami simplifikasi isu ataupun personalisasi dalam konflik. Apalagi bila materi konten berupa masalah yang kompleks tapi disuguhkan secara ringkas, dibarengi kalimat provokatif, dan ditambah dengan gambar atau video emosional yang menggantikan argumentasi rasional, alih-alih publik teredukasi, yang ada malah publik menjadi menjadi terpancing emosinya, perdebatan menjadi datar, reaktif, dan justu kehilangan kedalaman analisis.
Gejala yang perlu diantisipasi kita bersama juga berkaitan dengan kemunculan trial by social media. Fenomena itu muncul tatkala individu maupun institusi dihukum secara sosial oleh banyak netizen. Dia diframing bersalah setelah peristiwa itu viral, tanpa proses klarifikasi yang utuh, tanpa verifikasi berlapis, maupun tanpa menempuh proses peradilan yang adil.
Bila kita menelusuri ke belakang, di Provinsi Jambi beberapa kali ditemukan unggahan video pendek ataupun potongan percakapan yang viral dan memicu kemarahan publik. Tak jarang ada video berujung pada doxing, perburuan identitas, dan serbuan komentar negatif penuh caci maki.