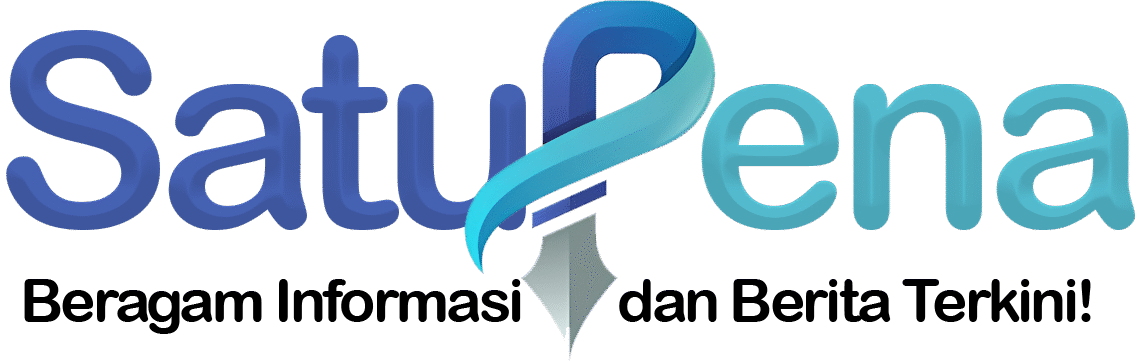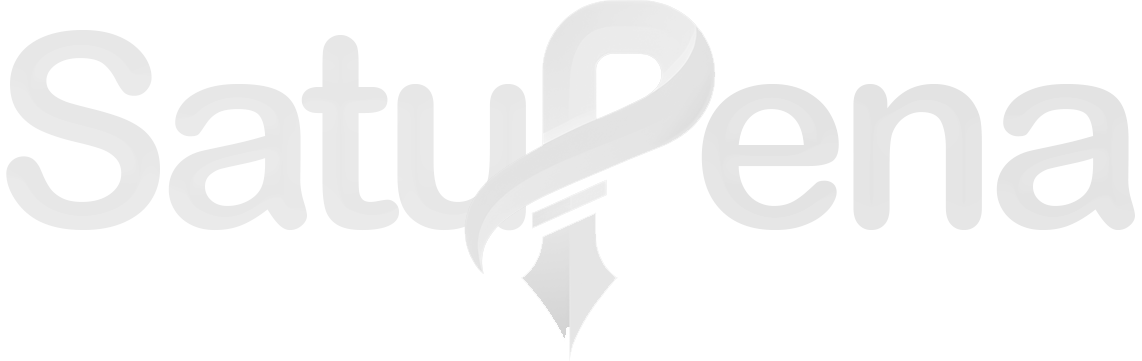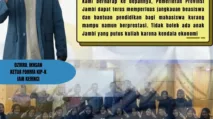Kerinci – Sebuah fenomena menarik tengah menyita perhatian pada saat ini, Aktivisme, yang dahulu dikenal sebagai mesin penggerak perubahan yang “lapar”, kini tampak kian dewasa atau barangkali, kian realistis.
Para pakar politik, termasuk sosiolog kritis Vedi Hadiz, kerap mencermati betapa struktur kekuasaan pasca Reformasi telah menjadi begitu “ramah” terhadap mereka yang dulu berada di seberang barisan. Bukan lagi dengan represi, namun dengan undangan terbuka untuk mencicipi manisnya hidangan di dalam sistem. Inilah yang secara satir sering disebut sebagai “Aktivisme Transaksional”.
Evolusi Suara: Dari Orasi ke Negosiasi
Sejarah mencatat bahwa suara yang paling lantang sering kali adalah suara yang paling lelah menahan lapar. Namun, dalam ekosistem patronase modern, kekuasaan tidak lagi memukul, namun ia memeluk. Melalui integrasi ke dalam jejaring kekuasaan, para pegiat yang dulu tajam bak sembilu kini perlahan melunak, bertransformasi menjadi mitra diskusi yang santun di bawah naungan rupiah.
“Ini bukan tentang kehilangan arah”, namun ini tentang perubahan metode. Mengapa harus berteriak di bawah terik matahari jika solusi bisa ditemukan sambil menyesap kopi mahal yang didanai oleh pihak yang sedang kita kritik?”
Pragmatisme yang Beretika?
Perdebatan antara Idealisme dan Pragmatisme kini bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal harga. Dalam kacamata sosiologi politik, integrasi mantan aktivis ke dalam jejaring patronase dipandang sebagai bentuk “pematangan” yang pragmatis.
Indikator keberhasilan gerakan tidak lagi diukur dari seberapa banyak kebijakan yang berubah demi rakyat, melainkan seberapa sering seorang aktivis diundang ke dalam “perjamuan” elit. Uang, dalam konteks ini, bukan lagi dianggap sebagai sogokan, melainkan ‘biaya operasional ketenangan.
Antara Katarsis dan Kompensasi
publik kini kerap disuguhi pemandangan unik sebuah orkestra perlawanan yang nadanya sangat terkontrol. Kritik tetap ada, namun volumenya telah disesuaikan dengan nilai transaksi yang disepakati.
Pada akhirnya, di tepi danau keresahan rakyat, banyak pejuang yang memilih untuk membasuh kaki mereka bukan dengan air mata keprihatinan, melainkan dengan kenyamanan yang dibeli oleh mereka yang mereka lawan. Karena bagi sebagian orang, menjadi “tajam” itu melelahkan, sementara menjadi “tumpul” di atas tumpukan materi adalah sebuah seni bertahan hidup yang paling elegan. (*)